Prolog
“Ada kalanya seorang lelaki pulang, tapi rumahnya sudah tak ada. Maka ia belajar membangun rumah baru di dalam hatinya sendiri—dan ia menamai rumah itu: rakyat.”
– Dedi Mulyadi
Malam-malam sunyi adalah teman yang jujur. Di antara cahaya remang dan bayang-bayang kenangan, aku belajar berbicara dengan diriku sendiri -tanpa mikrofon, tanpa kamera, tanpa tepuk tangan. Hanya ada satu suara yang tak pernah pergi: suara rakyat.
Aku pernah punya istri. Perempuan yang baik, lembut dan kuat. Tapi hidup tidak selalu mengikuti harapan. Kadang-kadang dua jalan yang dulunya saling bersisian, kini berpisah arah. Aku tidak ingin menyesali perpisahan. Yang kupelajari adalah bahwa cinta bisa berganti bentuk. Dan cinta sejati tak pernah mati, ia hanya mencari tempat tinggal baru.
Kini, setiap ibu yang menggigil menunggu bantuan di pelosok desa, setiap anak yang memeluk harapan sambil bersekolah dengan sandal jepit, setiap bapak yang tetap tersenyum walau sawahnya kering, mereka adalah keluargaku. Mereka adalah bagian dari cintaku yang tak terputus.
Benar, aku tak lagi punya seorang istri dalam arti konvensional. Tapi aku punya rakyat. Dan dalam setiap laku pengabdian, setiap keputusan yang menyentuh perut dan hati orang kecil, aku merasa seperti seorang suami yang bertanggung jawab: menjaga, melindungi dan mencintai mereka sepenuh hati.
Kini aku hidup menduda. Tapi aku tidak sendiri.
Anak Kampung Bernama Dedi
Aku lahir di sebuah kampung kecil di Subang, Jawa Barat. Tak banyak yang bisa dibanggakan dari tempat itu secara materi. Tapi justru di sanalah aku pertama kali belajar arti hidup: dari tanah, dari angin, dari bau kayu bakar dan dari wajah-wajah tulus yang tak kenal topeng sosial.
Bapakku bukan pejabat. Ibuku bukan pengusaha. Tapi mereka kaya dalam hal yang tak bisa dibeli, yakni rasa hormat kepada sesama, rasa cinta pada budaya dan rasa takut kepada Tuhan. Di rumah, kami tak banyak bicara soal uang. Yang dibicarakan adalah tetangga yang sedang kesusahan, sawah yang gagal panen atau siapa yang akan turun ke got untuk gotong royong besok pagi.
Aku tumbuh sebagai anak yang lebih suka mendengar. Duduk di bale-bale bambu sambil menyimak cerita kakek tentang karuhun. Atau menatap ibu menumbuk padi sambil melantunkan tembang sunda yang seperti doa panjang. Di situlah aku tahu jika rakyat bukan sekadar angka statistik. Mereka punya rasa, punya harapan dan sering kali cuma itu yang mereka miliki.
Ketika aku berjalan kaki ke sekolah dengan sepatu robek, aku tidak merasa miskin. Karena aku tahu, kemiskinan yang sesungguhnya adalah ketika seseorang kehilangan rasa peduli. Dan kampungku, sekalipun miskin secara harta, tapi tak pernah kekurangan kepedulian.
Aku menyimpan itu semua dalam hati. Dan ketika suatu hari aku berada di panggung politik, suara-suara kampung itu tak pernah benar-benar hilang. Mereka ada di belakang kepalaku, mengingatkan, menegur dan kadang membisikkan: “Jangan lupa, kamu anak kampung.”
Aku memang orang kampung. Tapi dari kampung itu, aku belajar bahwa kepemimpinan bukan soal titel, tapi soal keberanian untuk tetap manusiawi ketika semua orang memilih jadi mesin.
Di Jalan Sunyi Menuju Kepemimpinan
Tidak ada yang membisikkan kepadaku: “Kelak kamu akan jadi pemimpin.” Hidupku mengalir seperti air, tak terencana, tapi selalu mencari celah untuk tetap bergerak. Kadang deras, kadang nyaris kering. Tapi aku selalu percaya, aliran yang jujur akan sampai ke muara yang benar.
Waktu muda, aku hanya ingin berguna. Bukan populer. Maka aku lebih suka mendengarkan keluhan warga daripada berbicara panjang di depan panggung. Aku tahu rasanya mengantri bantuan beras. Aku tahu bagaimana malu yang tersembunyi di balik senyum seorang bapak yang tak bisa bayar SPP anaknya. Karena aku pun pernah ada di posisi itu.
Perjalanan menuju panggung kekuasaan bukanlah jalan tol. Tapi jalan setapak yang berliku, licin dan kadang sepi. Banyak yang datang dengan janji, lalu pergi bersama kekuasaan. Tapi aku memilih jalan sunyi, jalan yang sering tidak dimengerti, bahkan oleh teman sendiri.
Aku memulainya dari bawah. Dari obrolan warung, dari pos ronda, dari acara tahlilan. Aku tidak membangun citra. Aku hanya hadir. Dalam dunia politik yang penuh pertunjukan, kehadiran tulus memang terasa asing. Tapi justru itu yang membuatku dikenang.
Satu per satu, pintu mulai terbuka. Aku jadi anggota dewan. Lalu kemudian jadi bupati. Tapi anehnya, semakin tinggi jabatan, semakin sunyi rasa di dalam hati. Ada saat-saat di mana aku merasa justru makin jauh dari orang-orang yang dulu aku perjuangkan. Panggung dan protokol membuatku seperti aktor dalam dunia yang bukan lagi milikku.
Maka aku mundur selangkah. Aku pakai sandal jepit, aku duduk di pinggir sawah, aku menyapa rakyat tanpa jas resmi. Itu bukan gimmick. Itu caraku menjaga kewarasan. Caraku bilang pada diriku sendiri: “Ingat, kamu bukan raja. Kamu cuma pelayan.”
Kepemimpinan, bagiku, bukan soal mengatur. Tapi soal mengerti. Dan tak mungkin mengerti rakyat kalau tak pernah duduk di tikar mereka, makan dari piring mereka dan mendengar keluh kesah yang tak pernah masuk berita. Aku memilih jalan sunyi. Tapi jalan sunyi itulah yang membawaku pada rakyat. Dan pada akhirnya, kepada diriku sendiri.
Istriku Adalah Rakyat
Ada satu malam yang tak akan pernah kulupa. Hening, tapi menusuk. Di tengah suara jangkrik dan udara dingin yang seharusnya menenangkan, aku duduk sendiri. Di ruang tamu rumah yang dulu penuh tawa keluarga, kini hanya ada bayang-bayang percakapan yang telah pergi.
Aku resmi bercerai.
Tak mudah menulis kalimat itu. Apalagi mengucapkannya. Tapi inilah kenyataannya: aku bukan lagi suami dalam arti rumah tangga. Aku lelaki sendiri. Bukan karena tak mampu mencintai, tapi karena hidup kadang menempatkan cinta pada tempat yang tak bisa dipertahankan.
Banyak orang berbisik jika politik, perbedaan prinsip, ego ataupun waktu yang saling salip yang menjadi penyebabnya. Tapi aku tak ingin menuduh. Tak ada pahlawan atau penjahat dalam perpisahan. Hanya ada dua hati yang tak lagi berjalan seirama. Dan jika cinta itu masih ada, biarlah ia bertransformasi menjadi doa yang diam-diam dipanjatkan, bukan sebagai pasangan, tapi sebagai sesama manusia.
Tapi manusia tak bisa hidup tanpa cinta. Aku tak bisa. Maka aku mencari lagi kepada siapa hatiku akan kutambatkan? Jawabannya datang pelan-pelan, lewat mata anak-anak yang kusapa di sekolah-sekolah pelosok. Lewat tangan keriput ibu-ibu di pasar yang menggenggam tanganku sambil berkata, “Punten Kang, ulah poho ka urang leutik.” Lewat bapak-bapak tua yang masih semangat membersihkan selokan tanpa diminta.
Di situ aku sadar, aku memang menduda, tapi aku tidak sendiri. Aku punya rakyat.
Rakyat itu, bukan sekadar massa. Mereka adalah wajah-wajah yang menyimpan cinta yang tak bersyarat. Mereka tidak menuntut rumah mewah, mereka hanya ingin air bersih. Mereka tidak menuntut jam tangan mahal, mereka hanya ingin jalan desa yang bisa dilalui motor. Mereka tidak memelukku dengan pelukan, tapi dengan kepercayaan. Dan kepercayaan itu lebih berat dari cincin kawin.
Maka sejak hari itu, aku tak lagi merasa kehilangan. Aku mengganti gelar “suami dari seorang wanita” dengan “suami dari rakyat”. Sebuah ikatan yang tak tercatat di KUA, tapi dicatat dalam suara hati. Aku berjanji untuk menjaga, melindungi dan mencintai mereka. Seperti seorang suami menjaga istrinya dalam susah dan senang, sehat dan sakit.
Kadang aku merasa bersalah. Kepada anak-anakku. Kepada mantan istriku. Tapi hidup bukan novel yang bisa diulang babnya. Kita hanya bisa menulis dengan jujur, dan berharap akhir ceritanya tetap indah meskipun bab-bab sebelumnya penuh luka.
Kini, setiap kali aku turun ke pasar, duduk di bale-bale bambu atau sekadar menyapu halaman rumah rakyat yang sederhana, aku merasa pulang. Karena rumahku bukan lagi bangunan. Rumahku adalah setiap wajah rakyat yang tersenyum karena merasa ditemani. Dan aku tahu, aku masih punya cinta.
Antara Rasa dan Negara
Ada dua dunia yang berjalan bersisian dalam hidupku: dunia rasa dan dunia negara. Yang satu bicara hati, yang satu bicara sistem. Yang satu penuh kelembutan, yang satu penuh perhitungan. Dan aku, seperti kebanyakan lelaki, berdiri di tengah keduanya, berusaha menjaga agar keduanya tidak saling menelan.
Menjadi pemimpin bukan berarti menjadi manusia setengah dewa. Di balik pangkat dan panggung, aku tetap seorang ayah, lelaki, manusia biasa yang butuh pelukan, butuh dimengerti dan butuh dicintai. Tapi negara tidak memberi ruang untuk lemah. Ia menuntut hadir, kapan pun dan di mana pun. Saat rakyat menangis, aku harus jadi bahu. Saat rakyat marah, aku harus jadi perisai. Saat rakyat senyap, aku harus jadi suara.
Di rumah, aku kadang hanya bisa menjadi bayangan. Tubuhku mungkin pulang, tapi pikiranku masih tersisa di jalanan, di dapur rumah warga yang tak lagi bisa masak karena tak bisa beli gas atau di ladang kering yang menunggu hujan. Maka bagaimana mungkin seorang suami bisa utuh kalau setiap hari hatinya tersobek oleh jeritan rakyat?
Inilah dilema yang tak mudah dijelaskan. Aku mencintai keluargaku. Tapi aku juga mencintai rakyatku. Dan dalam banyak hari, cinta itu bukan berjalan beriringan, tapi saling tarik menarik. Rasa di rumah meminta waktu. Tapi negara menuntut tanggung jawab.
Dulu aku mencoba membagi diriku menjadi dua bagian: satu untuk keluarga, satu untuk rakyat. Tapi aku segera sadar, tubuh manusia tak bisa dibelah dua. Akhirnya, yang satu akan merasa ditinggal. Dan itulah luka yang hingga kini masih kupikul dalam diam.
Apakah aku menyesal? Tidak. Tapi aku belajar. Belajar bahwa pengabdian harus dibarengi pengertian. Bahwa menjadi pemimpin bukan berarti meninggalkan semua rasa, tapi justru menumbuhkannya, dengan cara yang lain, yang lebih luas, yang kadang tidak dipahami oleh orang-orang terdekat.
Ada malam-malam di mana aku ingin sekali menjadi orang biasa. Pulang kerja, makan bareng keluarga, ngobrol ringan tanpa bawa masalah rakyat. Tapi kemudian aku ingat, ada jutaan orang yang tidak bisa memilih jadi biasa. Mereka sudah ditakdirkan menjadi rakyat kecil. Dan kalau mereka tidak bisa memilih takdir mereka, aku pun tidak pantas mengeluh tentang takdirku.
Maka aku pasrahkan rasa kepada Tuhan. Dan kutunaikan tugas kepada rakyat. Jika suatu hari ada yang berkata bahwa aku terlalu mencintai rakyat sampai melupakan keluarga, maka biarlah itu jadi risalah hidupku. Karena bagiku, rasa dan negara bukan dua pilihan. Keduanya adalah luka yang kuterima sebagai bagian dari cinta yang lebih besar.
Tradisi, Karuhun dan Jalan Pulang
Banyak orang mengira politik adalah urusan strategi dan kekuasaan. Tapi bagiku, politik adalah jalan pulang. Pulang ke asal-usul. Pulang ke akar. Pulang ke karuhun yang diam-diam menuntun langkah, walau tubuh mereka sudah lama menyatu dengan tanah.
Aku tumbuh dalam kebudayaan Sunda. Bukan Sunda yang hanya tampil di panggung 17 Agustusan, tapi Sunda yang hidup dalam laku harian, dalam tata krama, dalam cara menyapa, dalam rasa hormat kepada yang lebih tua, dalam percaya bahwa alam ini bukan sekadar benda mati tapi bagian dari keluarga batin.
Di saat dunia politik menggoda dengan glamor dan kekuasaan, aku memilih memakai iket. Bukan sekadar hiasan kepala, tapi simbol dari kewaspadaan batin dan rasa malu kepada para leluhur. Di saat banyak pejabat bicara dengan jargon global, aku memilih bahasa ibu, bahasa rakyat. Karena aku percaya: yang datang dari hati, hanya bisa sampai ke hati jika dibahasakan dengan cinta yang dikenal oleh tanah sendiri.
Aku sering menyendiri ke gunung atau lembur-lembur terpencil, bukan untuk pencitraan, tapi untuk mengendapkan rasa. Dalam sunyi, aku mendengar bisik karuhun: “Anaking… ulah poho. Anjeun teh titipan, lain anu boga.”
(Anakku… jangan lupa. Kamu itu hanya titipan, bukan pemilik.)
Itulah sebabnya aku tak pernah terlalu terikat pada jabatan. Karena jabatan itu fana. Tapi hubungan batin antara pemimpin dan rakyat, antara anak dan karuhun, antara manusia dan tanah air, itulah yang abadi.
Sering aku termenung di tepi sawah. Menyaksikan petani yang menanam padi sambil bersenandung lemah. Mereka tak tahu apa itu APBN. Mereka tak peduli debat di televisi. Tapi dari ujung tangan mereka, kehidupan bangsa ini disambung. Dari peluh mereka, negeri ini diberi makan.
Aku bertanya dalam hati: “Apakah kita masih menghormati yang seperti ini? Ataukah kita terlalu sibuk mengejar popularitas dan lupa pada leluhur yang dulu menanam padi sambil berdoa?”
Politik yang tercerabut dari akar budaya hanya akan jadi mesin. Dinginnya logika akan mengalahkan hangatnya nurani. Maka aku memilih jalan yang mungkin dianggap lambat, tapi penuh rasa yakni jalan para karuhun. Jalan yang melihat rakyat bukan sebagai angka, tapi sebagai keturunan dari mereka yang dulu menanam pohon, mengalirkan sungai dan merawat harmoni.
Kadang orang mencibir, “Ah, itu romantisme.” Tapi bagiku, tanpa rasa, politik akan kehilangan arah. Seperti keris tanpa warangka, seperti pohon tanpa akar, seperti pemimpin tanpa jiwa. Dan aku tak ingin mati sebagai politikus. Aku ingin pulang sebagai anak Sunda.
Politik Itu Lelakon, Bukan Panggung
Sejak kecil, aku diajarkan satu nilai penting oleh karuhun: urip teh leumpang dina leuweung, hidup itu berjalan di hutan. Tak selalu terang, tak selalu lurus. Tapi kalau hati dijaga, langkah pasti sampai.
Maka ketika aku masuk ke dunia politik, aku tak melihatnya sebagai panggung hiburan. Aku melihatnya sebagai lelakon, sebuah laku hidup. Di dunia wayang, tokoh-tokohnya bukan sekadar karakter, tapi simbol dari perjuangan batin manusia. Ada waktu kita jadi Semar: bijak, diam tapi penuh makna. Ada waktu kita jadi Arjuna: ragu dan terombang-ambing. Dan kadang, kita harus menjadi Gatotkaca: turun dan bertempur demi kebenaran.
Sayangnya, dunia politik hari ini terlalu sering dijadikan panggung. Semua diukur dari seberapa viral, seberapa banyak sorakan, seberapa cepat trending. Tapi aku percaya jika yang benar tak selalu ramai, dan yang ramai tak selalu benar.
Aku memilih menjadi aktor dalam lelakon, bukan dalam panggung. Karena panggung butuh penonton, tapi lelakon hanya butuh kesetiaan pada peran. Dan peranku adalah menjaga nurani rakyat. Ada hari-hari di mana aku turun ke pasar bukan untuk pencitraan, tapi karena aku tahu, kalau aku tak menyapa mereka, siapa yang akan tahu bahwa harga beras naik? Kalau aku tak menyentuh lumpur sawah, bagaimana aku bisa bicara soal subsidi pupuk dengan sungguh-sungguh?
Tentu aku tidak sempurna karena aku bukan malaikat. Tapi aku selalu berusaha agar setiap keputusan politikku tidak lahir dari tekanan partai, tapi dari suara rakyat yang diam-diam berbicara lewat kesederhanaan mereka. Dan seringkali, suara paling jujur bukan datang dari ruang rapat, tapi dari ibu penjual gorengan yang berkata lirih:
“Kang, nu penting mah ulah ngajual nasib rakyat.”(Kang, yang penting jangan menjual nasib rakyat.)
Kalimat itu bagiku lebih tajam dari debat akademis. Lebih membekas dari standing ovation di acara formal. Karena kalimat itu lahir dari hidup yang nyata, bukan dari naskah.
Politik sebagai lelakon menuntut satu hal yakni kesetiaan. Bukan pada jabatan, tapi pada jiwa. Bukan pada institusi, tapi pada nilai. Lelakon mengajarkan bahwa kekuasaan itu bukanlah puncak, tapi beban. Semakin tinggi kita berdiri, semakin ringan tubuh harus kita bawa. Agar tidak sombong. Agar tidak lupa daratan.
Karena itulah aku tidak ingin diingat sebagai politisi sukses. Aku hanya ingin dikenang sebagai orang yang pernah setia pada lelakon hidupnya. Karena bagi orang seperti aku, politik bukanlah profesi. Politik adalah jalan untuk pulang.
Penutup
Cinta yang Tak Pernah Pergi
Aku pernah mencintai seseorang dengan seluruh hatiku. Kami berbagi tawa, duka, anak dan harapan. Lalu waktu mengubah arah angin. Kami bukan lagi dua kapal yang bisa berlayar berdampingan. Tapi cinta itu, tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya berubah bentuk. Menjadi kenangan. Menjadi doa. Menjadi pelajaran.
Setelah semua itu, aku hidup sendiri. Tapi aku tidak merasa sepi. Karena aku menemukan cinta yang lebih luas, lebih dalam dan lebih senyap: cinta kepada rakyat. Mereka tak memanggilku dengan kata manis. Tapi mereka menatap dengan harap. Mereka tidak memelukku setiap malam. Tapi mereka menaruh tanganku dalam kepercayaan. Mereka tidak memintaku untuk menjadi sempurna. Tapi mereka berharap aku tidak mengingkari mereka.
Cinta rakyat adalah cinta yang tak banyak berkata-kata. Tapi terasa dalam tiap langkah. Saat aku turun ke jalan, duduk di dipan bambu, tidur di rumah reyot atau makan dari piring seng, aku tahu, aku sedang menjalani bagian dari cinta itu.
Kadang aku rindu pada bentuk cinta yang dulu: rumah, istri, makan malam keluarga. Tapi hidup memberiku jalan lain. Jalan yang lebih sunyi, tapi tidak hampa. Karena dalam tiap napas pengabdian, aku merasa seperti seorang suami yang sedang berusaha setia.
Setia, meski tidak dipuji.
Setia, meski tak selalu dimengerti.
Setia, meski kadang sendiri.
Dan jika suatu saat tubuh ini lelah, dan tak lagi kuat berdiri di tengah rakyat, aku ingin dikenang bukan sebagai pejabat, bukan sebagai politisi, bukan sebagai mantan bupati, bukan sebagai seorang gubernur dengan penduduk 50 juta jiwa. Aku ingin dikenang sebagai seorang lelaki biasa yang pernah mencintai rakyatnya dengan seluruh hati.
Istriku pernah pergi. Tapi cinta tidak. Ia hanya berpindah tempat. Ia kini tinggal di pelupuk mata rakyat yang menua tanpa jaminan. Di suara anak-anak kecil yang berlari di tanah tanpa sekolah. Di senyum para petani yang tak pernah meminta imbalan.
Dan selama cinta itu masih hidup di dada, aku tak akan benar-benar sendiri. Karena istriku adalah rakyat.



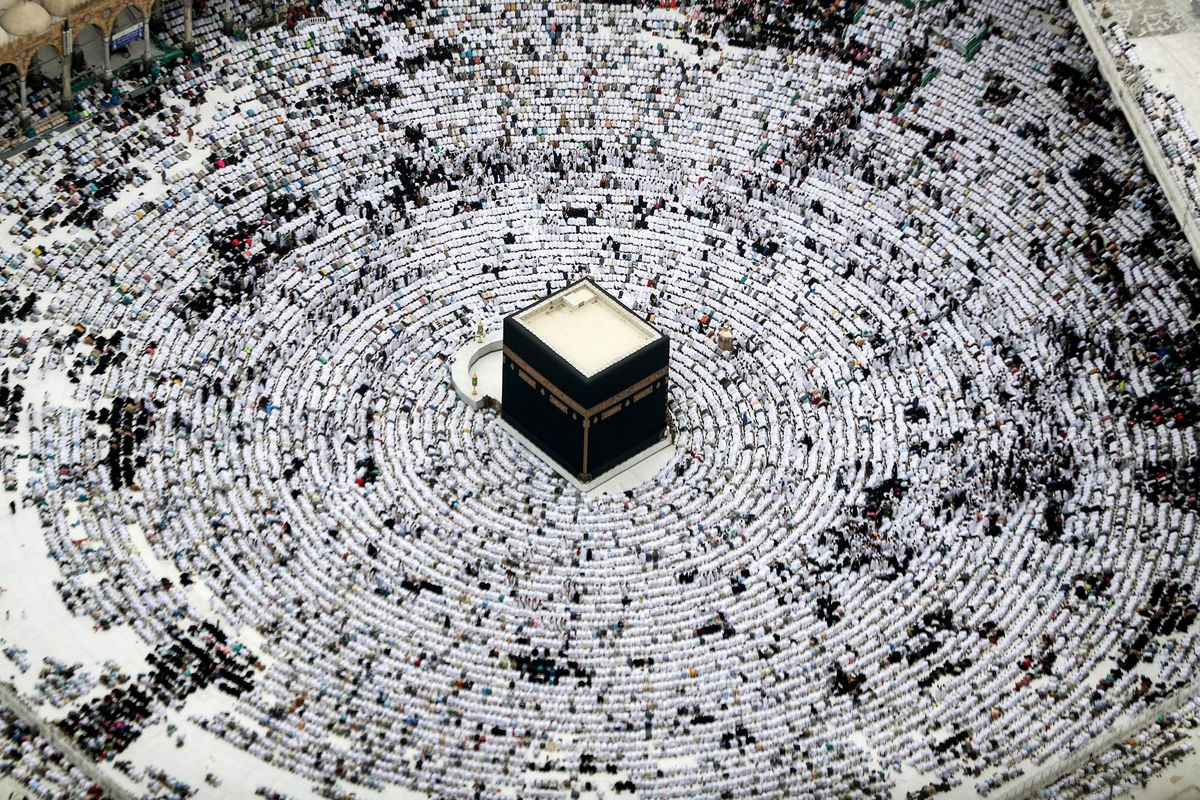




Leave a Reply